Tribunners / Citizen Journalism
Fenomena Rojali-Rohana, Cermin Retaknya Mesin Konsumsi Kelas Menengah
Fenomena Rojali dan Rohana bukanlah sekadar gaya belanja atau tren sosial musiman, ini adalah sinyal peringatan dini.
Editor:
Theresia Felisiani
Fenomena Rojali-Rohana, Cermin Retaknya Mesin Konsumsi Kelas Menengah
Oleh Tri Wibowo Santoso, Analis Ekonomi dan Politik di Lembaga Studi Data dan Informasi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Fenomena Rojali dan Rohana—rombongan jarang beli dan hanya nanya-nanya—bukanlah sekadar gaya belanja atau tren sosial musiman.
Ini adalah gejala ekonomi yang lahir dari kombinasi faktor struktural dan psikologis yang saling menguatkan, dengan akar masalah yang terhubung langsung ke data makroekonomi resmi.
Indikator-indikator seperti pertumbuhan uang beredar (M2), inflasi, dan pengeluaran konsumsi rumah tangga menunjukkan bahwa daya beli masyarakat memang sedang mengalami tekanan serius.
Pertumbuhan jumlah uang beredar (M2) sejak awal 2025 menunjukkan tren pelambatan. Bank Indonesia mencatat M2 pada Mei 2025 hanya tumbuh 4,9 persen year-on-year, lebih rendah dibandingkan Januari yang mencapai 5,9%.
Angka ini bukan sekadar statistik; pelambatan likuiditas berarti uang yang berputar di masyarakat untuk konsumsi, investasi, dan tabungan semakin terbatas.
Kondisi ini selaras dengan laporan BPS yang mencatat bahwa kontribusi konsumsi rumah tangga terhadap PDB mulai stagnan, dengan belanja barang non-pokok mengalami perlambatan.
Baca juga: Kiat Mal Hadapi Rojali dan Rohana, Berikan Stimulus kepada Pengunjung Agar Berbelanja
Di saat uang beredar melambat, inflasi menekan dari sisi lain. Inflasi umum mungkin terlihat terkendali di kisaran 2–3%, tetapi inflasi pangan dan jasa cenderung lebih tinggi, sehingga memukul daya beli riil masyarakat.
Fenomena shrinkflation, di mana ukuran barang mengecil atau kualitas dikurangi tanpa penurunan harga, membuat konsumen semakin hati-hati mengeluarkan uang. Data BPS memperlihatkan pola pengeluaran rumah tangga yang bergeser: porsi belanja kebutuhan pokok meningkat, sementara porsi untuk rekreasi, pakaian, dan barang tahan lama menurun.
Beban biaya hidup yang melonjak tanpa diimbangi kenaikan pendapatan memperparah situasi. Harga pangan, sewa tempat tinggal, transportasi, dan biaya pendidikan naik, sementara upah riil relatif stagnan.
Data BI menunjukkan rasio utang rumah tangga terhadap PDB meningkat, didorong oleh cicilan KPR, kendaraan, hingga pinjaman konsumtif berbasis digital seperti paylater.
Ini menjelaskan mengapa mal tetap ramai oleh Rojali dan Rohana—bukan pembeli aktif, tetapi pengunjung yang sekadar memanfaatkan fasilitas pendingin udara dan spot foto gratis.
Ketimpangan antara realitas ekonomi dan narasi pembangunan makin tajam ketika kita melihat kondisi iklim investasi.
Pajak yang tinggi, pungutan resmi dan tidak resmi, serta beban biaya logistik dan premanisme industri membuat investor asing mengalihkan modal ke negara-negara tetangga seperti Thailand dan Vietnam, yang menawarkan produktivitas tenaga kerja lebih tinggi, birokrasi lebih sederhana, dan risiko usaha lebih rendah.
Akibatnya, sektor manufaktur padat karya di Indonesia kehilangan basisnya, menyusutkan lapangan kerja formal dan mendorong eksodus pekerja ke sektor informal dengan pendapatan tak menentu. Kondisi ini menciptakan siklus ekonomi yang menggerus konsumsi.
Tribuners adalah platform jurnalisme warga. Untuk berkontribusi, anda bisa mengirimkan karya dalam bentuk berita, opini, esai, maupun kolom ke email [email protected]
Konten menjadi tanggungjawab penulis dan tidak mewakili pandangan redaksi tribunnews.com.


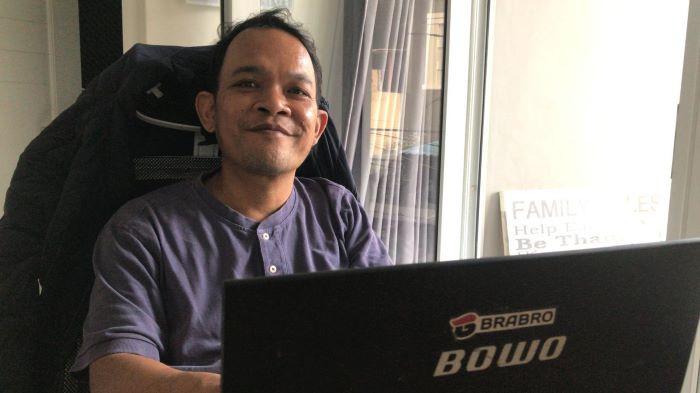



















Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.