Tribunners / Citizen Journalism
Keadilan Sosial, Hukum, dan Kesalahan Memahami Ketimpangan
Banyak sekali kebijakan sosial di Indonesia justru lahir dari tekanan kelompok tertentu, bukan dari kajian komprehensif berbasis data.
oleh Dr. Bakhrul Amal, S.H., M.Kn.
Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta
TRIBUNNEWS.COM - Thomas Sowell, dalam bukunya Social Justice Fallacies, mengatakan satu hal yang penting untuk kita renungkan yakni perihal "tidak semua ketimpangan adalah ketidakadilan."
Banyak kebijakan sosial modern, menurut Sowell, dibangun di atas asumsi yang keliru bahwa setiap perbedaan "pendapatan" di antara masing-masing individu atau kelompok itu selalu disebabkan oleh diskriminasi sistemik.
Padahal kenyataannya tidak demikian. Perbedaan "pendapatan" itu seringkali juga muncul karena permasalahan yang lebih kompleks dari sekedar mendistribusikan kekayaan.
Gagasan ini relevan dengan situasi Indonesia hari ini. Pemerintah dan pembuat undang-undang seringkali merancang kebijakan atas dasar asumsi bahwa setiap kelompok yang tertinggal harus dibantu melalui aturan afirmatif.
Di sinilah Sowell memberi kritik tajam. Sowell melihat bahwa kebijakan yang terlalu fokus pada tujuan untuk membuat "masyarakat harus setara" justru sering mengabaikan faktor penyebab terjadinya ketidaksetaraan itu sendiri.
Faktor penyebab dimaksud seperti faktor budaya kerja, kualitas pendidikan, struktur sosial atau bahkan permasalahan di dalam keluarga.
Contoh di Indonesia
Sebagai contoh, laporan BPS tahun 2023 menunjukkan bahwa Indeks Ketimpangan (Gini Ratio) Indonesia stagnan di angka 0,388. Angka 0,338 memang bukan angka yang ekstrem.
Namun angka itu cukup menunjukkan bahwa ada ketimpangan pendapatan di masyarakat kita.
Namun, jika kita telusuri lebih jauh, ketimpangan itu terjadi bukan karena adanya perbedaan terhadap distribusi kekayaan yang dilakukan oleh pemerintah.
Pada laporan lain, yakni pada data PISA 2022 dari OECD, kemampuan membaca siswa Indonesia berada pada peringkat ke-69 dari 81 negara.
Baca juga: Kontestasi Pemilihan dan Keadilan Sosial
Jika dikaitkan dengan paragraf sebelumnya, maka dapat kita simpulkan ketimpangan kualitas pendidikan di berbagai daerah jauh lebih tajam daripada ketimpangan pendapatan.
Ketimpangan ini, atau ketimpangan dalam kualitas pendidikan, merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi hasil pandapatan seseorang dalam jangka waktu yang lebih panjang.
Nahasnya, pendekatan kebijakan yang diambil oleh pemerintah justru sering menyepelekan akar masalah seperti ini.
Alih-alih memperbaiki mutu pendidikan, pemerintah dan pembuat undang-undang lebih banyak mengatur tentang standar kebutuhan hidup, insentif, dan diakhiri dengan pemberian bantuan langsung tunai.
Dengan kata lain, negara justru lebih fokus mengatur distribusi kekayaan daripada membuat kebijakan untuk memperbaiki kualitas dan kapasitas masyarakat.
Sowell menyebut kecenderungan ini sebagai bentuk intelektualisme moral. Intelektualisme moral adalah bentuk dorongan kuat untuk terlihat adil di masyarakat meski itu dilakukan tanpa riset yang jelas.
Banyak sekali kebijakan sosial di Indonesia justru lahir dari tekanan kelompok tertentu, bukan dari kajian komprehensif berbasis data.
Di Indonesia, pola ini bisa dilihat dari proses penyusunan regulasi yang terburu-buru, minim partisipasi publik dan kurang mengandalkan kajian tentang dampak sosial.
Memanfaatkan Kekuatan Hukum
Hukum, sebagai sarana melegalisasi tindakan, adalah objek yang seringkali menjadi tameng bagi pemerintah untuk menegaskan “keadilan”, meski sekedar keadilan dalam bentuk simbolik.
Misal, undang-undang dibuat untuk menjamin hak kelompok tertentu tetapi tanpa disertai mekanisme penjaminan hak yang benar-benar efektif.
Padahal dalam beberapa kasus, aturan afirmasi terkadang justru melahirkan dampak negatif berupa ketergantungan.
Contohnya dapat dilihat dari data Kemenko PMK yang menunjukkan bahwa 60 persen peserta Program Keluarga Harapan (PKH) tidak mengalami kenaikan kelas sosial yang signifikan.
Padahal itu telah berlangsung selama lebih dari 5 tahun menjadi penerima manfaat. Artinya banyak bantuan yang diberikan kepada masyarakat, termasuk yang bersifat rutin, berakhir mubazir.
Bantuan itu diberikan, tetapi tidak cukup mampu untuk mendorong perubahan kondisi kehidupan masyarakat.
Di sinilah pentingnya pendekatan hukum yang lebih realistis. Hukum tidak cukup sekadar menyatakan niat baik.
Ia harus mampu membaca dinamika masyarakat, membedakan antara ketimpangan yang wajar dan ketimpangan yang lahir dari diskriminasi struktural.
Tidak semua disparitas atau kesenjangan adalah masalah yang harus diselesaikan dengan membuat aturan "penyetaraan".
Sebab kadang ketidaksetaraan merupakan gejala yang timbul dari masalah sosial, ekonomi, atau budaya yang lebih kompleks.
Sowell bukan sedang menolak upaya mewujudkan keadilan sosial. Ia justru mengingatkan agar keadilan tidak dijalankan dengan cara yang salah. Ia mendorong pendekatan berbasis fakta, bukan prasangka.
Dalam konteks Indonesia, pendekatan seperti ini masih jarang diadopsi. Hukum cenderung reaktif, mengikuti tekanan wacana, dan kurang mengandalkan evaluasi berbasis data jangka panjang.
Penutup
Atas kenyataan tadi, maka sesungguhnya tantangan praktisi maupun akademisi hukum ke depan bukan hanya soal merancang hukum yang baik dan berpihak. Namun juga memastikan bahwa aturan keberpihakan itu tepat sasaran dan berbasis data.
Gagasan Thomas Sowell memberikan kita inspirasi, pengalaman beserta koreksi penting bahwa upaya mewujudkan keadilan sosial itu membutuhkan kajian yang mendalam.
Membutuhkan kesediaan untuk bisa membedakan antara ketimpangan yang perlu diintervensi oleh hukum dan ketimpangan yang wajar terjadi dalam masyarakat yang beragam.
Tanpa sikap itu, hukum berisiko kehilangan fungsi utamanya sebagai instrumen pengatur yang rasional dan adil.
Hukum malah mungkin bisa tergelincir menjadi sarana kebijakan populis yang tidak efektif, bersifat politis, menambah ketergantungan dan sulit dievaluasi dampaknya secara nyata. (*)

Sumber: TribunSolo.com
Tribuners adalah platform jurnalisme warga. Untuk berkontribusi, anda bisa mengirimkan karya dalam bentuk berita, opini, esai, maupun kolom ke email [email protected]
Konten menjadi tanggungjawab penulis dan tidak mewakili pandangan redaksi tribunnews.com.
| Minta Pemda Tingkatkan Kualitas SDM, Mendagri: Kalau Berhasil Indonesia jadi Negara Dominan |

|
|---|
| Menkeu Pindahkan Dana Rp 200 Triliun ke Bank Himbara, Gubernur BI: Perkuat Injeksi Likuiditas |

|
|---|
| Emil Audero Masuk Best XI Serie A Pekan 3, Statistiknya Ungguli David De Gea |

|
|---|
| 4 Sosok Potensial Calon Ketua PSSI Jika Erick Thohir Lepas Jabatan Usai Dilantik Jadi Menpora |

|
|---|
| Sorotan 32 Besar China Masters 2025 Tunggal Putra: Kejutan Alwi Tak Terjadi, Harapan Tinggal di Jojo |

|
|---|




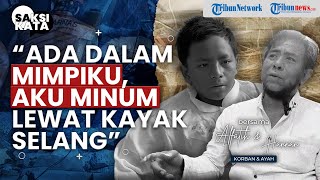
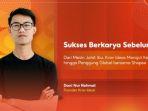














Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.