Pilot Project Pilah Sampah di Kabupaten Bandung, Anak Muda Jadi Motor Penggerak Perubahan Lingkungan
Kabupaten Bandung tengah menghadapi tantangan serius dalam pengelolaan sampah.
TRIBUNNEWS.COM, BANDUNG - Kabupaten Bandung, sebagai bagian dari kawasan metropolitan Bandung Raya, tengah menghadapi tantangan serius dalam pengelolaan sampah.
Bersama Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kota Cimahi, wilayah ini sangat bergantung pada Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sarimukti di Kabupaten Bandung Barat—yang menjadi titik akhir pembuangan sampah regional Jawa Barat.
Ketergantungan ini membuat Kabupaten Bandung sangat rentan terhadap gangguan operasional di TPA.
Ketika Sarimukti mengalami kelebihan kapasitas, kebakaran, atau penutupan sementara, dampaknya langsung terasa: sampah menumpuk di TPS, jadwal pengangkutan terganggu, bahkan sebagian warga terpaksa membakar atau menimbun sampah sendiri.
Masalah ini bukan hanya soal lingkungan dan kesehatan, tetapi juga memicu tekanan sosial dan ekonomi yang menuntut solusi cepat dari pemerintah daerah.
Situasi tersebut mendorong Kabupaten Bandung untuk mencari strategi baru.
Tidak cukup hanya mengandalkan pengangkutan ke TPA, kini saatnya mengurangi sampah dari sumbernya—melalui pemilahan, pengolahan mandiri, dan pemanfaatan kembali material yang masih bernilai.
Tantangan Pengelolaan Sampah: Potret Kabupaten Bandung
Meski bergantung pada TPA Sarimukti, kesadaran masyarakat untuk memilah sampah dari rumah masih rendah.
Kebiasaan memilah belum terbentuk secara luas, sehingga peran kelembagaan lingkungan seperti bank sampah dan pengurus kebersihan RT/RW belum optimal.
Keterbatasan dana juga menjadi hambatan dalam penyediaan sarana pendukung seperti tempat sampah terpilah, komposter, dan armada pengangkut.
Pemerintah daerah sebenarnya telah menerbitkan regulasi terkait pemilahan sampah dari sumber.
Namun, lemahnya implementasi dan minimnya pengawasan membuat kebijakan tersebut belum berjalan efektif.
Tantangan pengelolaan sampah di Kabupaten Bandung mencakup lima aspek utama: teknis, kelembagaan, pendanaan, partisipasi masyarakat, serta regulasi dan kebijakan yang belum bersinergi.
Baca juga: Depok Dorong Warga Ubah Kebiasaan, Mulai Pilah Sampah dari Rumah
ISWMP dan PPAM: Kolaborasi untuk Perubahan
Pengelolaan sampah kini bukan lagi sekadar urusan teknis.
Melalui program Improvement of Solid Waste Management to Support Regional and Metropolitan Cities Project (ISWMP), pemerintah pusat bersama Bank Dunia mendorong reformasi menyeluruh dalam sistem persampahan daerah.
Tujuannya: menciptakan tata kelola sampah yang terintegrasi, partisipatif, dan berkelanjutan.
Salah satu pendekatan utama ISWMP adalah Peningkatan Peran Aktif Masyarakat (PPAM).
Program ini memulai perubahan dari lingkungan terkecil—dengan membangun kesadaran, membentuk sistem lokal, dan melibatkan warga untuk memilah sampah langsung dari rumah.
Kolaborasi lintas kementerian dan pemerintah daerah memperkuat sistem ini.
Dukungan diberikan melalui penguatan regulasi, perencanaan adaptif, dan pembinaan kelembagaan lokal.
Kelima aspek pengelolaan sampah ditangani secara terpadu:
- Teknis: Pemilahan dari rumah, pengelolaan sampah organik dengan LCO dan komposter, serta penjualan sampah anorganik ke pengepul.
- Kelembagaan: Pembentukan tim pengelola berbasis RT oleh Karang Taruna Burujul 002.
- Pendanaan: Swadaya masyarakat dan pemanfaatan hasil penjualan sampah sebagai dana operasional komunitas.
- Partisipasi: Sosialisasi berjenjang, pelatihan teknis, dan pemasangan stiker rumah sebagai penanda partisipasi.
- Regulasi dan sinergi: Pendampingan dari DLH, Puskesmas, aparatur desa, serta penguatan komitmen antar-OPD.
Menurut Oki Suyatno, Kepala Bidang Persampahan DLH Kabupaten Bandung, pendekatan ISWMP yang menekankan edukasi dan pendampingan langsung telah membawa dampak positif.
“ISWMP hadir untuk mengubah perilaku masyarakat terkait sampah, dengan konsep edukasi dan pendampingan langsung. Kami ingin menggeser budaya lama kumpul-angkut-buang menjadi pengelolaan yang lebih terencana dan berdampak,” ujarnya.
Perubahan ini memang tidak instan.
Ada tahapan transisi perilaku yang harus dilalui: dari mencoba, melaksanakan, menjaga konsistensi, hingga mampu mengajak orang lain ikut serta. Selain membawa perubahan gaya hidup, pendekatan ini juga berdampak nyata secara ekonomi dan operasional.
“Harapan kami, setelah sampah berhasil dipilah dari sumbernya, masyarakat akan merasakan manfaat langsung. Di sisi lain, kami sebagai pemerintah daerah juga dapat menekan biaya operasional,” tambah Oki.
Cerita dari Lapangan: RT 02 RW 17 Desa Mekar Rahayu
Di Desa Mekar Rahayu, Kecamatan Margaasih, perubahan besar dimulai dari lingkungan kecil.
Sejak Desember 2024, PPAM menggulirkan pilot project pengelolaan sampah di RT 02 RW 17—lingkungan padat dengan 98 Kepala Keluarga.
Dengan fasilitas sederhana seperti ember bekas cat untuk sampah organik dan karung bekas untuk anorganik, warga mulai dikenalkan pada konsep pilah sampah dari rumah.
Karang Taruna menjadi ujung tombak: menimbang, mencatat hasil pilahan, dan mendistribusikan sampah ke pengepul. Hasil penjualan digunakan untuk mendukung kegiatan komunitas.
Hingga Januari 2025, 37 KK telah aktif memilah sampah secara rutin. Warga yang sebelumnya pasif kini mulai mandiri, bahkan menyadari nilai ekonomi dari sampah anorganik.
Kunci keberhasilan bukan hanya pada sarana, tetapi pada kolaborasi.
Kader kesehatan dan posyandu turut menyuarakan pentingnya kebersihan lingkungan. Sistem insentif pun diterapkan, mengaitkan kontribusi pemilahan sampah dengan kesehatan ibu dan anak.
Cerita dari RT 02 RW 17 membuktikan bahwa perubahan bisa dimulai dari skala terkecil—asal ada komitmen, partisipasi, dan semangat gotong royong.
Jika pola ini direplikasi ke desa lain, beban TPA bisa ditekan dan sistem pengelolaan sampah berkelanjutan bisa menjadi milik bersama.
Menuju Replikasi dan Keberlanjutan
Meski masih tahap awal, masyarakat Desa Mekar Rahayu telah membuktikan bahwa perubahan nyata bisa dimulai dari komunitas kecil.
Program ini membuka jalan menuju sistem pengelolaan sampah yang murah, mudah, dan berkelanjutan—tanpa bergantung pada teknologi mahal.
Upaya replikasi kini dirancang untuk menjangkau RW lain melalui edukasi tatap muka, kampanye media sosial, dan gerakan “Warga Memilah Sampah” yang digagas pemerintah daerah.
Anak muda, khususnya Karang Taruna, menjadi motor penggerak: mengajak tetangga, menimbang hasil pilahan, dan mengelola penjualan sampah untuk membiayai kegiatan komunitas.
Dukungan dari pemerintah desa dan DLH Kabupaten Bandung memperkuat langkah ini, dengan penyediaan sarana pemilahan, pembentukan peraturan desa, dan menjadikan Mekar Rahayu sebagai contoh praktik baik bagi wilayah lain.
Kisah Mekar Rahayu menunjukkan bahwa pengelolaan sampah bukan soal teknologi, melainkan soal kemauan untuk berubah, rasa memiliki, dan semangat gotong royong.
Jika semangat ini terus diperluas dan direplikasi, mimpi Bandung Raya “Merdeka dari Sampah” bukan lagi sekadar wacana—tetapi target yang bisa dicapai bersama.
| Pria Bertato di Padalarang Bandung Nyaris Dihakimi Massa, Diduga Lakukan Pencabulan Anak |

|
|---|
| Tunjangan Perumahan Rp54 Juta, Ketua DPRD Kabupaten Bandung: Dipotong Pajak |

|
|---|
| Ada Orang Misterius Datang Sebelum Ibu dan Dua Anaknya Tewas di Rumah Kontrakan Bandung |

|
|---|
| Isi Surat Wasiat Ibu yang Meninggal Bersama 2 Anaknya di Bandung: Lelah Hidup Terlilit Utang |

|
|---|
| Ibu dan 2 Anaknya Ditemukan Tewas di Bandung, Tinggalkan Secarik Surat untuk Suami |

|
|---|









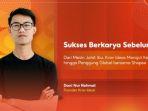










Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.