Tribunners / Citizen Journalism
Hari Lahir Pancasila
Ketahanan Budaya dalam Pemikiran Soekarno: Memaknai 80 Tahun Lahirnya Pancasila
Pancasila bukan hanya sintesis politik, tetapi gema kebudayaan yang menyatukan perasaan kolektif bangsa.
Ketahanan Budaya dalam Pemikiran Soekarno: Memaknai 80 Tahun Lahirnya Pancasila
Oleh: Yulis Susilawaty
Analis Pertahanan dan Geopolitik Di Indonesian Public Institute (IPI)
PEMIKIRAN Bung Karno sebagai Proklamator dan Presiden pertama Republik Indonesia menyimpan jejak intelektual dan spiritual yang dalam terhadap fondasi budaya bangsa.
Di tengah kemajemukan etnis, agama, bahasa, dan adat istiadat di Nusantara, Bung Karno memahami bahwa budaya adalah perekat paling kuat untuk menjahit tenun kebangsaan Indonesia.
Ia tidak hanya merumuskan Pancasila sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai cerminan jiwa bangsa yang berakar pada nilai-nilai budaya lokal.
Mengulas pemikiran budaya Soekarno melalui pendekatan konseptual dan reflektif, dengan menyoroti bagaimana resonansi budaya menjadi kunci utama dalam membangun identitas nasional.
Pancasila sebagai Resonansi Budaya
Pidato Soekarno pada 1 Juni 1945 yang memperkenalkan Pancasila menjadi penanda bahwa dasar negara Indonesia lahir dari proses perenungan mendalam terhadap realitas kebudayaan bangsa. Ia berkata:
“Saudara-saudara, saya katakan: dasar negara, yakni dasar falsafah negara, dasar pikiran yang sedalam-dalamnya, haruslah digali dari dalam bumi Indonesia sendiri” (Soekarno, 1945).
Soekarno tidak mengadopsi ideologi dari Barat maupun Timur secara mentah, melainkan meraciknya dari nilai-nilai yang sudah lama hidup dalam masyarakat.
Konsep gotong royong, musyawarah mufakat, serta keadilan sosial adalah manifestasi budaya lokal yang diangkat menjadi prinsip negara.
Pancasila bukan hanya sintesis politik, tetapi gema kebudayaan yang menyatukan perasaan kolektif bangsa.
Resonansi budaya dalam Pancasila berfungsi sebagai sistem makna yang membimbing bangsa melalui transformasi zaman. Nilai-nilai luhur ini bersifat organik dan terus beresonansi dalam praktik kehidupan masyarakat Indonesia.
Dalam konteks budaya, Pancasila adalah bentuk “resonansi nilai” yang mampu menyatukan suara beragam kelompok. Ia menjadi jembatan yang menghubungkan identitas-identitas kultural menjadi satu narasi kebangsaan (Suryomenggolo, 2013).
Nation and Character Building: Membangun Karakter Bangsa
Bung Karno mengembangkan gagasan nation and character building sebagai proses pembentukan identitas bangsa yang merdeka dan bermartabat. Ia percaya bahwa bangsa yang baru merdeka harus melepaskan mentalitas inferior yang diwariskan kolonialisme. Membangun jati diri kolektif adalah pekerjaan kebudayaan.
Simbol-simbol seperti Bahasa Indonesia, Bendera Merah Putih, dan Garuda Pancasila dipilih bukan karena keseragaman, tetapi karena kemampuannya mewakili semangat kebhinekaan. Soekarno juga kerap mengutip kejayaan Sriwijaya dan Majapahit sebagai bukti bahwa bangsa Indonesia pernah jaya dan dapat kembali bangkit (Noer, 1980).
Soekarno memandang Pancasila sebagai hasil sintesis historis dan sosiokultural bangsa Indonesia.
Ia menggali “mutiara” dari bumi Nusantara—nilai-nilai yang tidak hanya hidup dalam sistem sosial, tapi juga dalam hati nurani rakyat Indonesia. Konsep ini menjadikan Pancasila sebagai hasil pengendapan budaya, bukan semata hasil intelektual elitis.
Konsep Revolusi Mental dan Pendidikan Kebudayaan
Meski istilah “revolusi mental” populer di era kontemporer, Soekarno telah lebih dulu menggaungkannya dalam makna esensial. Ia menginginkan perubahan mentalitas bangsa yang sebelumnya terjajah menjadi bangsa yang merdeka secara psikologis dan intelektual. Melalui pidato-pidato, pendidikan politik, dan penggunaan bahasa rakyat, Bung Karno mengajak bangsa Indonesia untuk berdikari dan percaya diri.
Ia menekankan pentingnya pendidikan dan propaganda yang membangun karakter bangsa, dengan memanfaatkan bahasa yang membumi, visualisasi simbol-simbol kebangsaan, serta pemanfaatan media massa sebagai sarana transformasi budaya. Dalam hal ini, resonansi budaya mengambil bentuk praksis: nilai-nilai hidup dan ditanamkan dalam keseharian, bukan hanya dikhotbahkan.
Seni dan Budaya sebagai Alat Pemersatu
Soekarno memandang seni bukan sekadar ekspresi estetika, tetapi sebagai medium perjuangan dan persatuan. Ia memfasilitasi tumbuhnya kesenian tradisional sekaligus mendorong karya-karya yang bersemangat revolusioner.
Festival budaya, pertunjukan seni daerah, dan penciptaan lagu-lagu perjuangan adalah bentuk politik kebudayaan yang ia orkestrasi (Hanan, 2014).
Resonansi budaya ini menciptakan ikatan emosional yang menjembatani perbedaan suku dan bahasa.
Dengan pengalaman bersama akan keindahan budaya masing-masing, lahirlah semangat persatuan yang otentik dan tidak dipaksakan. Dalam konteks ini, kebudayaan berperan sebagai mediator sosial yang menjaga integrasi nasional.
Trisakti: Pilar Kebudayaan dalam Kemandirian Bangsa
Dalam konsep Trisakti, Soekarno mengajukan tiga pilar utama: berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.
Pilar ketiga menjadi penekanan bahwa identitas budaya adalah benteng terhadap pengaruh asing yang dapat mengikis jati diri bangsa.
"Kita ingin menjadi bangsa yang berkepala tegak, tidak minder, dan tidak latah" (Soekarno, 1963).
Trisakti adalah visi integral yang menggabungkan kekuatan politik, ekonomi, dan budaya. Relevansinya semakin terasa di era globalisasi yang sarat dengan disrupsi nilai. Soekarno menekankan bahwa tanpa karakter kebudayaan yang kuat, bangsa akan kehilangan arah dan mudah terombang-ambing oleh kepentingan eksternal.
Di sinilah pentingnya konsep ketahanan budaya, yaitu kemampuan bangsa mempertahankan identitas dan sistem nilai lokal di tengah tekanan globalisasi yang massif. Ketahanan budaya bukan sekadar perlindungan terhadap warisan masa lalu, melainkan keberlanjutan narasi kebangsaan yang adaptif dan tangguh. Soekarno memproyeksikan budaya sebagai kekuatan strategis, bukan simbolik semata. Trisakti menjadikan budaya sebagai pilar daya tahan bangsa—penjaga integritas di tengah kompetisi nilai dan hegemoni informasi global.
Pancasila sebagai Platform Bersama di Era Digital
Di tengah era digital yang menghadirkan fragmentasi informasi, nilai-nilai Pancasila kembali menjadi jembatan yang menyatukan. Soekarno menekankan pentingnya memelihara gotong royong dan musyawarah sebagai roh dari kebersamaan nasional.
Untuk menjangkau generasi muda, nilai-nilai Pancasila perlu dikemas dalam format konten kreatif: film, musik, podcast, dan media sosial yang tidak hanya informatif tetapi juga emosional dan membumi.
Semangat pidato Bung Karno yang membakar semangat massa bisa diterjemahkan ke dalam gaya komunikasi yang disukai anak muda.
Dalam era ini, resonansi budaya tidak lagi bersifat linier, melainkan interaktif dan dialogis. Generasi digital bisa menjadi pelaku budaya sekaligus pencipta makna baru dari nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, pendekatan edukatif dan komunikatif harus beradaptasi dengan semangat zaman.
Pancasila dalam Konteks Global dan Diplomasi Budaya
Pancasila juga diperkenalkan kepada dunia dalam pidato Bung Karno di Sidang Majelis Umum PBB tahun 1960 berjudul To Build the World Anew. Dalam pidato itu, ia menawarkan Pancasila sebagai jembatan alternatif antara dua kutub ideologi besar dunia: kapitalisme dan komunisme.
Nilai-nilai seperti keadilan sosial, persatuan dalam keberagaman, dan musyawarah memiliki resonansi universal dan relevan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan dan hak asasi manusia. Pidato ini bahkan diakui UNESCO sebagai Memory of the World.
Diplomasi budaya Indonesia yang berbasis Pancasila menjadikan bangsa ini sebagai aktor penting dalam perdamaian dunia dan penguatan multilateralisme, khususnya melalui ASEAN, Gerakan Non-Blok, dan forum-forum global lainnya. Resonansi budaya dalam diplomasi ini memperkuat narasi bahwa Indonesia bukan hanya penonton, tetapi aktor dengan kontribusi khas terhadap perdamaian dunia.
Tantangan dan Rekomendasi
Dalam konteks kebangsaan modern, ketahanan budaya menjadi aspek vital dari ketahanan nasional secara keseluruhan. Ia mencakup kemampuan sistem nilai, simbol, bahasa, dan praktik budaya lokal untuk tetap hidup, berkembang, dan diteruskan lintas generasi. Pemikiran Soekarno menempatkan budaya sebagai fondasi strategis yang tidak hanya membentuk identitas bangsa, tetapi juga menjadi tameng terhadap infiltrasi nilai-nilai yang berpotensi melemahkan jati diri nasional.
Meski pemikiran budaya Soekarno masih sangat relevan, implementasinya menghadapi sejumlah tantangan kontemporer.
Pertama, globalisasi dan digitalisasi telah membawa budaya luar yang sering kali tidak sejalan dengan nilai-nilai lokal, menyebabkan krisis identitas dan degradasi nilai.
Kedua, lemahnya sistem pendidikan kebudayaan di sekolah formal membuat generasi muda kehilangan akar budayanya.
Ketiga, politik identitas yang berkembang justru bertolak belakang dengan semangat persatuan dalam keberagaman yang dijunjung Pancasila.
Sebagai solusi, diperlukan sejumlah langkah strategis:
- Revitalisasi Pendidikan Budaya dan Pancasila: Pemerintah perlu menanamkan kembali nilai-nilai kebangsaan secara holistik sejak pendidikan dasar hingga tinggi melalui metode yang partisipatif dan kontekstual.
- Penguatan Ekosistem Budaya Digital: Mendorong generasi muda memproduksi konten digital yang menggali nilai-nilai lokal dan tokoh nasional seperti Bung Karno dengan pendekatan kreatif dan populer.
- Pemanfaatan Diplomasi Budaya Progresif: Pemerintah dan pegiat budaya perlu mengembangkan jejaring internasional berbasis nilai-nilai Pancasila untuk membangun narasi Indonesia di kancah global.
- Perlindungan dan Pengembangan Warisan Budaya: Memberikan insentif terhadap pelaku seni tradisional dan lembaga adat sebagai penjaga nilai-nilai budaya lokal yang menjadi dasar resonansi kebangsaan.
Kesimpulan
Pemikiran budaya Soekarno tidak hanya relevan untuk masa lalu, tetapi juga menjadi kompas moral untuk masa depan Indonesia. Dalam memperingati 80 tahun lahirnya Pancasila, penting untuk meresapi kembali bagaimana Soekarno menempatkan budaya sebagai ruh bangsa.
Ia tidak sekadar membangun negara secara struktural, tetapi juga menata batin bangsa melalui resonansi nilai yang berasal dari budaya lokal.
Pancasila, Trisakti, dan strategi kebudayaan Soekarno adalah warisan yang harus terus dihidupkan melalui pendidikan, kebijakan, dan praktik sosial.
Dengan begitu, resonansi budaya tidak menjadi gema kosong, tetapi nadi yang memompa ketahanan bangsa di tengah dunia yang terus berubah. (*/)
Tribuners adalah platform jurnalisme warga. Untuk berkontribusi, anda bisa mengirimkan karya dalam bentuk berita, opini, esai, maupun kolom ke email [email protected]
Konten menjadi tanggungjawab penulis dan tidak mewakili pandangan redaksi tribunnews.com.
Hari Lahir Pancasila
| Hendri Satrio Sebut Prabowo Bijaksana Tak Tempatkan Gibran di Depan Megawati |
|---|
| Megawati-Gibran Bertemu di Hari Lahir Pancasila, Interaksi Mereka Dinilai Buat Publik Penasaran |
|---|
| Prabowo Ingatkan Ancaman Adu Domba dari Luar, Singgung LSM-LSM |
|---|
| Masih Penyembuhan, Jokowi Tak Hadir Upacara Hari Lahir Pancasila di Jakarta |
|---|
| Momen Akrab Prabowo, Megawati, dan Gibran Sebelum Ikuti Upacara Hari Lahir Pancasila |
|---|




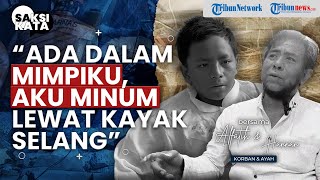
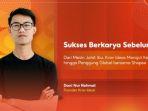














Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.