Tribunners / Citizen Journalism
Mengingat Kembali Pangkal Persoalan Rohingya: Kekerasan Harus Dihentikan
Gelombang pengungsian ini tidak akan terjadi apabila kekerasan tidak terus berlangsung di Myanmar. Kekerasan harus segera dihentikan.
Oleh: Eva Nila Sari (Penulis adalah Pegawai Komisi Nasional Hak Asasi Manusia)
TRIBUNNERS - Terombang-ambingnya nasib ratusan ribu warga etnis Rohingya, bahkan gaduhnya penolakan terhadap mereka, mengarahkan kita pada polemik perlu tidaknya penghormatan atas kemanusiaan yang diwarnai dengan kerumitan yang bahkan ditimbulkan oleh para pengungsi ini.
Namun entah mengapa opini yang berkembang terkesan mengabaikan pangkal persoalan yaitu tidak dihentikannya aksi pembersihan etnis atas warga Rakhine yang dilakukan oleh Tentara Myanmar. Alhasil gelombang Pengungsi Rohingya terus mengalir, utamanya ke negara-negara seperti Bangladesh, India, Thailand, Malaysia dan Indonesia.
Sebagaimana diberitakan, sejumlah negara telah menerima dan menolak para pengungsi ini. Banyak faktor yang terlibat dalam penolakan tersebut, seperti tidak sanggup dengan ledakan jumlah pengungsi yang datang, hingga pengungsi yang tidak menaati norma setempat atau bahkan terlibat aksi kriminal.
Gelombang pengungsian ini tidak akan terjadi apabila kekerasan tidak terus berlangsung di Myanmar. Kata kunci yang paling logis adalah kekerasan harus segera dihentikan.
Rumor yang Diyakini sebagai Kebenaran
Kaki tangan Inggris, demikian persepsi yang berkembang di kalangan warga Budha Myanmar atas warga etnis Rohingya.
Keyakinan ini, selama bertahun-tahun, telah dijadikan sebagai alasan pembenar untuk melakukan kekerasan bahkan hingga hari ini (kendati telah sekian tahun merdeka dari Inggris).
Fakta bahwa mereka (Rohingya) juga dapat digolongkan sebagai warga lokal karena telah menempati Myanmar (yang dulunya Burma) sejak Abad ke-12, tidak menjadi faktor penting yang patut dipertimbangkan.
Nama Rohingya diperkenalkan pertama kali pada literatur Inggris tahun 1799 yang ditulis oleh Francis Buchanan Hamilton (ahli fisika dan geografi) yang menyebutkan Rooinga atau mereka yang lama tinggal di Arakan atau warga asli Arakan.
Eksodus etnis Rohingya pertama kali terjadi pada tahun 1785, kala itu konflik Meletus di Arakan (sekarang Rakhine) akibat penguasaan oleh etnis Bamar secara opresif.
Banyak warga Rohingya yang lari ke Bangladesh (masih dalam peguasaan Inggris).
Penguasaan Inggris di Myanmar dimulai pada tahun 1823 yang ditandai oleh pembukaan lahan teh secara besar-besaran. Dalam rangka itu, Inggris mendatangkan tenaga kerja dari India dan Bangladesh.
Mereka membangun hidup baru di Myanmar dengan pekerjaan dan pendapatan yang layak.
Tak hanya mendatangkan banyak imigran dari India dan Bangladesh yang notabene beragama Islam, Pemerintah Kolonial Inggris juga tidak terlihat mendukung eksistensi raja-raja Burma, bahkan mengangkat lebih banyak warga muslim untuk menduduki posisi di pemerintahan.
Bagi warga Budha Myanmar hal ini dianggap sebagai bentuk ketidakadilan karena mereka menilai Inggris lebih membela orang Islam (Rohingya) dan di benak mereka, orang Islam merebut banyak hal di tanah Myanmar.
Tak pelak, gesekan etnis mulai terjadi di Burma.
Warga Budha semakin jengah dengan kondisi ini yang dikemudian hari terbukti menjadi bahan bakar untuk memerdekakan diri dari Inggris. Nasionalisme yang dibangun berdasarkan solidaritas sesama penganut Budha kian tumbuh dan menggelora menjadi api perlawanan yang terbukti telah membebaskan mereka dari cengkraman kolonialisme Inggris.
Bersamaan dengan itu, solidaritas berdasar agama ini juga turut menekan kelompok Rohingya yang diposisikan antagonis dan menjadi bagian dari kolonialisme Inggris.
Demonisasi atas Rohingya terjadi hanya berdasar asumsi bahwa mereka akan menguasai Myanmar karena dinilai hidup lebih makmur dan terus tumbuh ketimbang warga Budha Myanmar.
Pada perkembangannya, kebencian atas etnis Rohingya semakin membuncah, tak lain karena (lagi-lagi) persepsi supremasi agama bahwa tanah Myanmar hanya diperuntukkan bagi warga Budha seperti halnya kaum Hindu yang menguasai tanah India.
Persepsi kebencian semakin diintrodusir dan disebarluaskan paska kemerdekaan Myanmar dari Inggris bahkan cenderung menjadi komoditas politik.
Betapa tidak, rezim junta militer telah memanfaatkan sentimen kebencian ini untuk melanggengkan kuasa mereka hingga konflik berevolusi menjadi konflik etnis dan agama yang terus menerus memakan korban. Bagi Junta militer, isu Rohingya ternyata cukup efektif dalam menggalang dukungan masyarakat Budha di Myanmar.
Diskriminasi terhadap Rohingya lantas dilegalkan ke dalam bentuk aturan. Secara resmi mereka telah dinyatakan sebagai etnis yang tidak diakui oleh negara.
Hal ini dimulai sejak Jenderal Ne Win mengkudeta Perdana Menteri U Nu pada tahun 1962 dan memerintah Myanmar setidaknya hingga tahun 2011. Alhasil etnis Rohingya mengalami persekusi selama puluhan tahun bahkan hingga hari ini. Ironinya, hal ini terjadi hanya karena maraknya rumor yang diyakini sebagai kebenaran.
Stateless
Pasca memerdekakan diri dari Inggris pada tahun 1948, Pemerintah Burma menerbitkan aturan mengenai siapa saja pihak yang berhak mendapatkan status kewarganegaan dan etnis Rohingya menjadi pengecualian.
Lalu pasca kudeta militer pada tahun 1962, negara mewajibkan semua warga membawa akses kartu registrasi nasional (semacam KTP), dan warga Rohingya hanya mendapatkan kartu identitas warga asing yang membatasi mereka dalam mengkakses hak atas pekerjaan dan pendidikan.
Pada tahun 1982, Pemerintah Junta Militer Burma bahkan menutup kesempatan bagi warga Rohingya dalam mendapatkan status kewarnegaraan. Kala ini diterbitkan undang-undang yang mengatur tiga bentuk kewarganegaraan.
Untuk mencapai tingkat yang paling dasar yaitu naturalisasi, diperlukan bukti telah mendiami Myanmar sejak sebelum tahun 1948 dan fasih menguasai salah satu bahasa nasional.
Persoalannya, warga Rohingya sangat kesulitan memegang bukti pra tinggal sebelum tahun 1948 karena Pemerintah Junta Militer tidak memasukkan etnis Rohingya ke dalam 135 etnis resmi di Myanmar, dan negara memposisikan Rohingya sebagai penduduk Bangladesh yang masuk ke Myanmar secara ilegal.
Langkah ini didukung oleh kesepakatan repatriasi tahun 1979 antara Pemerintah Bangladesh dan Myanmar yang sesungguhnya merupakan pengembalian pengungsi Rohingya ke Myanmar karena ketidaksanggupan Pemerintah Bangladesh menampung para pengungsi tersebut.
Pada tahun 1990-an, etnis Rohingya diberi kartu identitas (white card) yang memberikan hak namun terbatas dan tidak berlaku sebagai bukti kewarganegaraan.
Singkat kata, sejumlah aturan yang telah diterbitkan tersebut telah menjauhkan etnis Rohingya dalam mengkases hak-hak kewarganegaraannya bahkan dalam bentuk yang paling dasar sekalipun.
Alhasil, pada titik tertentu Pemerintah berkuasa di Myanmar telah menempatkan etnis ini dalam posisi stateless.
Alhasil, Rohingya telah menjadi etnis terbesar di dunia yang tidak memiliki kewarnegaraan.
‘Perlawanan Itu Akhirnya Terjadi’
Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres telah menyatakan bahwa bencana kemanusiaan dalam bentuk genosida dan serangan brutal junta militer telah berlangsung di depan mata warga Rohingya. Kondisi ini telah menyebabkan ratusan ribu orang Rohingya mengungsi dari negaranya.
Yang tinggal pun tak sanggup lagi menahan derita yang sangat mendalam ini. Tak terhindarkan, Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA) akhirnya melakukan serangan berdarah di sejumlah Pos Polisi dan Tentara pada tahun 2017.
Junta Militer Myanmar pun merespon keras serangan tersebut yang kemudian meluncurkan aksi balasan berskala besar. ARSA kemudian dinyatakan sebagai kelompok teroris.
Junta militer telah menyatakan sejumlah pembenaran tersebut untuk bertindak brutal, bahkan menarget warga sipil yang tidak terlibat apapun. Desa dibumihanguskan, warga sipil diperkosa, ditembak, disiksa, diculik, dibunuh.
Eksodus tak terelakkan. Pada gilirannya, PBB kemudian menyatakan Junta Militer telah menerapkan taktik genosida yang tentu saja dibantah oleh mereka.
ARSA adalah kelompok pemberontak yang berdiri tahun 2016. Sebelumnya menamakan diri Harakatul Yakeen. Aksi pertama dilancarkan pada tahun 2016 dengan menyerang 3 (tiga) pos polisi di Maungdaw dan Rathedaung. 9 (Sembilan) Polisi tewas pada aksi tersebut.
ARSA adalah reaksi atas tindak penindasan Pemerintah Myanmar terhadap warga Rohingya selama berpuluh-puluh tahun. ARSA hadir ingin membela warga Rohingya yang secara sistematis telah dijauhkan dari penikmatan hak-hak dasarnya.
Klaim keterkaitan ARSA dengan ISIS dan Al-Qaeda seketika dibantah. Pemimpin ARSA Ataullah Abu Amar Jununi, sekali lagi, menyatakan kalau itu propaganda yang menyudutkan perjuangan ARSA dan rakyat Rohingya.
Maung Zarni (European Centre for the Study of Ekstremism) menegaskan bahwa ARSA bukanlah teroris melainkan sekumpulan orang-orang putus asa yang memutuskan melawan tiran dan melindungi warga Rohingya yang puluhan tahun hidup dalam kesengsaraan.
Gerakan Kebencian
Cukup banyak penyebar kebencian yang bekerja mengenalkan, menyebarkan dan memupuk kebencian atas Rohingya yang notabene mayoritas penganut Muslim. Adalah Wirathu, seorang biksu yang menjadi pentolan pada gerakan anti-Islam. Ia mempunyai andil terhadap seruan persekusi atas kelompok agama minoritas, khususnya Rohingya.
Cara yang ia lakukan beragam, salah satunya adalah membuat propaganda anti-Rohingya di Facebook yang isinya ajakan mengusir warga Rohingya.
Pada Juli 2013 sosoknya menjadi sampul majalah TIME dengan tajuk “Wajah Teror Buddhis”. Sosok ini telah memperkenalkan ultranasionalisme yang dibalut bungkus agama. Sosok ini sangat lekat dengan seruan persekusi kelompok agama minoritas khususnya Rohingya.
Ia menjadi biksu sejak usia 14 tahun. Karirnya sebagai bisku semakin mentereng sejak menjadi pentolan Gerakan 969 yang dimulai sejak tahun 2001. Gerakan ini terbentuk dan membesar karena persepsi bahwa Muslim di Myanmar mempunyai misi khusus dalam mendirikan negara khilafah.
Ia mengklaim orang-orang Islam di Myanmar tak terkecuali Rohingya sedang membesarkan diri sehingga menjadi ancaman yang menggerogoti nilai-nilai Budha dan negara Myanmar.
Kebenciannya pun tak sekedar kata-kata tanpa makna karena ia sangat aktif menuangkan bahan bakar kepada masyarakat Myanmar untuk memboikot produk dan toko-toko milik muslim.
Pada 2003 ia divonis 25 tahun penjara, karena akibat hasutan kebencian anti Islam yang ia prakarsai, telah menyebabkan tewasnya 10 (sepuluh) orang muslim. Namun tak lama berselang, ia pun dibebaskan.
Pasca gerakan ARSA tahun 2017 pun, Wirathu memainkan sentimen anti Rohingya secara total. Salah satu senjata andalannya adalah facebook. Melalui platform ini ia menjaring puluhan ribu pendukung dan kelompok militan. Konten-kontennya berisi ajakan mengusir, menyudutkan dan menegaskan sebagai kelompok berbahaya.
Intinya segala bentuk disinformasi yang mendorong publik menyimpulkan bahwa etnis Rohingya ini jahat dan berbahaya. Ia pun menegaskan bahwa ihwal pengusiran baik yang dilakukan oleh Junta Militer maupun publik adalah bentuk nasionalisme. Propagandanya melalui facebook, terlanjur menyebar dan membangkitkan sel-sel kelompok biksu ektremis lainnya.
Pada 2019, ia kembali didakwa melakukan penghasutan kepada pemerintahan sipil Myanmar di bawah komando Aung San Suu Kyi dan NDL nya. Namun dua tahun kemudian ia dibebaskan junta militer setelah berhasil mengkudeta pemerintahan Suu Kyi. Tak hanya dibebaskan dari segala dakwaan, Wirathu bahkan diganjar penghargaan Thiri Pyanchi dan dinyatakan berkontribusi pada persatuan dan kesatuan Myanmar.
“Tak Ada Jalan Lain Selain Mencari Tempat Berlindung….”
Pengungsian warga Rohingya tak terelakkan. Tindak persekusi dan kekerasan selama puluhan tahun dan tidak diberikannya status kewarganegaraan (stateless), sesungguhnya telah menyudutkan warga Rohingya dan tidak lagi menemukan tempat berlindung bahkan di negaranya sendiri.
Tak ada jalan lain selain meninggalkan negeri asalnya dan mengadu nasib di negeri-negeri asing yang mungkin belum pernah dikunjungi seumur hidup mereka.
PBB mencatat sedikitnya 1.752 pengungsi Rohingya yang sebagian besar merupakan perempuan dan anak-anak, telah tiba di Indonesia sejak pertengahan November 2023 hingga akhir Januari 2024. PBB mengatakan lonjakan kali ini adalah arus masuk terbesar sejak tahun 2015.
PBB juga mengatakan bahwa lebih dari 3.500 warga Rohingya diyakini telah melakukan perjalanan penuh risiko ke negara-negara Asia Tenggara pada tahun 2022 dan hampir 1.000 warga Rohingya dilaporkan meninggal dunia atau hilang sejak awal tahun 2022, dalam percobaan menyeberang laut yang berbahaya.
Di Malaysia, lebih dari 100.000 pengungsi Rohingya hidup sebagai masyarakat yang terpinggirkan. Banyak dari mereka bekerja secara ilegal di bidang konstruksi dan pekerjaan berupah rendah lainnya.
Data United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) dan International Organization for Migration (IOM) menyebutkan, secara akumulatif kurang lebih 1,5 juta orang Rohingya telah mengungsi sejak tahun 1970 dan jumlahnya terus meningkat secara signifikan pasca konflik meledak tahun 2017.
Sejumlah 900 ribu sd 1 juta orang Rohingya mengungsi ke Bangladesh, 153.000 orang mendarat di Malaysia, 850.000 orang Rohingya mengungsi di negaranya sendiri (Myanmar), 50.000 orang melarikan diri ke India, masing-masing 5000 orang ke Thailand dan Australia serta 1000 orang melarikan diri ke Indonesia.
Bangladesh bukanlah tujuan ideal pengungsian. Faktor geografis yang dekat dengan Myanmar membuat Bangladesh menjadi tujuan pengungsian yang realistis. Tidak perlu menyebrangi lautan dan tinggal menuju ke perbatasan. Lokasi pengungsian berpusat di Cox’s Bazar dan telah dibangun 33 kamp pengungsian. Telah menampung lebih dari 900.000 orang.
Cox’s Bazar jauh dari kata layak, sanitasi buruk, air yang dipakai untuk kebutuhan sehari-hari terkontaminasi dengan bakteri. Tak sedikit yang terjangkit diare dan mengalami keracunan.
Pada 2017, tercatat 10 (sepuluh) pengungsi yang tewas akibat difteri, sekitar 200.000 orang menempati rumah yang rawan hancur apabila cuaca berubah buruk. Lokasi ini tergolong sangat padat, Pemerintah Bangladesh sendiri mengaku kewalahan dengan intensifnya arus pengungsian dan bersepakat dengan Pemerintah Myanmar untuk melakukan repatriasi atau pengembalian pengungsi secara bertahap.
Namun ini pun persoalan lain, mereka mengalami trauma dan ketakutan bakal dipersekusi untuk kesekian kali apabila kembali ke negaranya.
Di titik ini banyak pengungsi Rohingya mencari jalan lain dengan mencari lokasi pengungsian di negara-negara sekitar Asia Tenggara termasuk Indonesia. Tentu saja dengan bertaruh menjadi korban human trafficking atau tenggelam di laut lepas. Bahkan potensi penolakan dan mengalami pengusiran pun sangat mungkin terjadi.
Bantahan Pemerintah Myanmar
Gambia, sebuah negara kecil di Afrika barat yang mayoritas penduduknya Muslim, telah membawa kasus Rohingya ke International Court of Justice (ICJ) atau Mahkamah Internasional atas nama puluhan negara Muslim lainnya.
Misi pencari fakta PBB yang menyelidiki tuduhan tersebut, menemukan bukti menarik yang menyatakan bahwa tentara Myanmar harus diselidiki untuk tuduhan genosida terhadap Muslim Rohingya di Rakhine.
Laporan hasil penyelidikan menyoroti berbagai temuan misi internasional independen yang mengungkap adanya "pelanggaran HAM berat dan pelanggaran yang diderita Muslim Rohingya serta minoritas lainnya" oleh pasukan keamanan Myanmar yang digambarkan sebagai "kejahatan paling berat di bawah hukum internasional". Temuan Tim PBB ini tentu saja dibantah oleh Pemerintah Myanmar.
Bantahan tersebut tidak menyurutkan Majelis Umum PBB dalam menerbitkan resolusi terkait nasib warga Rohingya. Resolusi disahkan pada 27 Desember 2019 oleh total 134 negara dari 193 negara anggota, sembilan suara menentang dan 28 lainnya abstain.
Resolusi PBB tersebut mengutuk pelanggaran hak asasi manusia terhadap Muslim Rohingya dan minoritas lainnya di Myanmar, menyerukan agar Myanmar menghentikan hasutan kebencian terhadap minoritas Rohingya dan kelompok minoritas lainnya, mendorong perlindungan terhadap semua kelompok, dan menjamin keadilan bagi semua korban pelanggaran hak asasi manusia.
Resolusi tersebut juga menyatakan kekhawatiran atas membanjirnya orang-orang Rohingya ke Bangladesh yang disebut sebagai “akibat kekejaman pasukan keamanan dan bersenjata Myanmar".
Kendati Resolusi Majelis Umum PBB ini telah secara jelas mengungkap tindak pelanggaran yang dilakukan Tentara Myanmar dan harapan penanganan yang harus segera diakukan oleh Pemerintah Myanmar, namun tidak berarti persoalan selesai. Pasalnya, Resolusi Majelis Umum PBB tidak mengikat secara hukum namun mencerminkan pendapat dunia.
Oleh karenanya aksi nyata masih sangat diperlukan. Pada level pergaulan dunia, baik di level regional maupun internasional, diplomasi masih terbukti mempunyai dampak. Pada konteks ini upaya advokasi khususnya melalui konsolidasi lembaga-lembaga dunia masih dibutuhkan, antara lain melalui forum ASEAN, OKI dan seterusnya.
ASEAN mempunyai akses untuk menekan Myanmar agar segera menghentikan aksi kekerasan atas warga Rohingya dan kaum minirotas lain. Bahkan dapat mempertimbangkan pembekuan keanggotaan negara Myanmar di ASEAN apabila dalam waktu yang dipandang cukup, kekerasan tidak juga dihentikan.
Langkah selanjutnya adalah mendesak Pemerintah Myanmar segera memformulasikan solusi baik jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.
Harapannya, warga Rohingya tidak lagi merasa tidak aman dan merasa perlu meninggalkan negaranya. Terkait para pengungsi yang sudah meninggalkan negaranya, perlu pula dipikirkan kelangsungan hidup mereka sehingga dapat kembali atau berdamai dengan kondisi dan situasi warga lokal di tempat baru. Konsolidasi ini sangat mungkin dilakukan, terlebih negara-negara tujuan masih terikat dalam komunitas regional Asean dan Asia Pasifik.
Pulau Bagi Warga Rohingya?
Indonesia memang belum meratifikasi ‘The 1951 Refugee Convention’ namun Indonesia memiliki legal framework bagi pemberian suaka atau perlindungan kepada para pengungsi.
Sebut saja Sila kedua Pancasila, Pasal 28G UUD 1945 (mengakui hak untuk memberikan suaka bagi semua orang), dan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 (mengatur penanganan pengungsi dari luar negeri al. menyediakan tempat penampungan bagi mereka terutama anak yang masuk dalam kategori pengungsi berkebutuhan khusus dan harus diberikan perawatan berdasarkan pada asas kepentingan terbaik).
Kesemua peraturan ini menjadi dasar bagi Pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan kepada para pengungsi yang datang ke wilayah kedaulatan Republik Indonesia.
Mengabaikan para pengungsi tersebut, sama saja dengan tidak menjalankan konstitusi yang berlaku di negara kita sendiri.
Pada satu kesempatan, United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) Perwakilan Indonesia menyebutkan bahwa Pengungsi Rohingya kerap menjadi sasaran kampanye kebencian yang terkoordinasi.
Juru bicara lembaga PBB ini juga menegaskan bahwa segala biaya yang disebabkan oleh para pengungsi akan ditanggung oleh UNHCR beserta para mitra dan tidak akan membebani pendanaan APBD maupun APBN.
Fenomena penolakan warga atas kedatangan para Pengungsi Rohingya seharusnya menjadi catatan terkait mekanisme apa yang dapat diterapkan untuk mengadvokasi para pengungsi ini. Pasalnya, terlalu sulit mengembalikan mereka ke negara asalnya. Namun perlu dipikirkan bagaimana Indonesia dapat menampung dan memberikan penghidupan kepada mereka atas nama kemanusiaan dan implementasi konstitusi.
Menempatkan masyarakat Etnis Rohingya pada suatu tempat/ kawasan khusus banyak diperbincangkan akhir-akhir ini. Lantas apakah langkah ini dapat dilakukan?
Ide ini pertama kali disampaikan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). MUI meminta Pemerintah Indonesia menyiapkan satu Pulau untuk menampung pengungsi Rohingya bila memungkinkan.
Sebelumnya Wakil Presiden Ma’ruf Amin sempat mewacanakan Pulau Galang sebagai lokasi penampungan warga etnis Rohingnya mengingat sebelumnya sempat diperuntukkan sebagai tempat penampungan pengungsi asal Vietnam. Namun ide ini serta merta ditolak Menkopolhukam Mafud MD dan menyatakan tengah dipertimbangkan lokasi lain untuk menampung manusia perahu ini.
Akan tetapi momen pilpres telah menghentikan wacana ini. Semoga segera berlanjut dengan langkah berikutnya pasca Pilpres 2024. (Eva Nila Sari)
Tribuners adalah platform jurnalisme warga. Untuk berkontribusi, anda bisa mengirimkan karya dalam bentuk berita, opini, esai, maupun kolom ke email [email protected]
Konten menjadi tanggungjawab penulis dan tidak mewakili pandangan redaksi tribunnews.com.
| Redmi 15 Siap Dijual 25 September: Layar 144Hz dan Baterai 7.000 mAh Jadi Senjata Utama |

|
|---|
| 229 Hotel di Bali Terancam Sanksi, KLH Ungkap Rapor Merah Pengelolaan Limbah |

|
|---|
| Terhanyut di Madura: Cerita Warga Australia Temukan Cinta di Tengah Selawat Santri |

|
|---|
| Pendaftaran BPI Beasiswa Pendidikan Indonesia untuk Guru serta Calon Guru D-4 atau S-1 |

|
|---|
| Indonesia–Polandia Teken Perjanjian MLA: Langkah Strategis Berantas Kejahatan Lintas Negara |

|
|---|




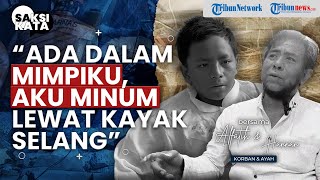
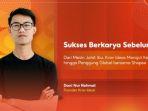














Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.