Tribunners / Citizen Journalism
KH Imam Jazuli: Kritik Nalar Atas Ideologi HTI
Sebagaimana negara kita punya Pancasila sebagai ideologi ideal karena negara kita multi etnis dan multi religi.
Karena itu, ditelisik dari sini, ayat ini terasa sangat jauh, jika terpaksa ditarik dengan perintah pendirian negara Islam (Khilafah). Apalagi, Abu Hurairah ra., menjelaskan asbabul nuzul ayat tersebut terkait dengan pembiaran terhadap orang Yahudi yang berzina. Az-Zuhri menyatakan, “Telah sampai kepada kami bahwa QS al-Maidah ayat 44 ini turun untuk mereka. Nabi saw., juga termasuk dari mereka (maksudnya ar-nabiyyun al-ladzina aslamu).” (HR Ahmad, Abu Dawud, dan Ibnu Jarir).
Dalam ayat sebelumnya, Allah Swt. mencela kaum Yahudi yang berpaling dari Taurat. Kerana tingkah-laku tersebut, mereka dinyatakan bukan bagian dari kaum beriman (ayat 43). (Al-Jazairi, Aysâr at-Tafâsîr li Kalâm, Nahr al-Khair, 1993, h. 635 dan As-Suyuti, Ad-Durr al-Mantsûr, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990, h. 506)
Ketiga, jika perintah berdakwah, amar-ma'ruf, nahi mungkar, sebagaimana tersurat pada ali-Imran, 104, diatas diantaranya harus ditempuh, terlebih dulu dengan mendirikan negara Islam (Khilafah), maka pengambilan hukum (istimbat) ini bersifat sangkaan (tsubut dilalah)).
Dalam bahasa Immanuel Kant, ia hanya hepotesa-fiktif, yang bersifat imperatif hipotetis. Para pakar Ushul-Fiqh mengingatkan, jangan sampai memahami teks/lafazd yang Am (umum), padahal maksudnya adalah Khas (khusus), atau sebaliknya, atau Muqayyad, padahal maskudnya Mutlaq, atau Manthuq dan Mafhum-nya berseberangan dan lain-lain, sehingga menimbulkan kerancauan.
Jumhur ulama sepakat, kewajiban pokok agama (muhakamat) harus bersumber dari dalil yang pasti, baik dalam riwayat, maupun dalam petunjuk.
Keempat, HTI yakin penegakan khilâfah adalah perintah agama yang diabaikan mayoritas kaum muslimin. Padahal, menurut mereka, Islam telah mewarisi Negara Madinah, sebagai miniatur sebuah bangsa yang dinamakan negara Islam (Khilafah). Problem mendasar dari argumen ini adalah, jika hal itu kewajiban, apalagi bersifat ushul, kenapa Nabi tidak meninggalkan prodak hukum yang bersifat baku, dan perundang-undangan yang terperinci, dan aplikatif terkait dengan keberlangsungan Negara Madinah?
Padahal, --sebagaimana kritik Khalil Abdul Karim, untuk masuk toiletpun seorang muslim mendapatkan bimbingan secara terperinci. Perlu dicatat, para teoritisi menyebutnya sebagai al-hakimiyah wa al-khilafah, terminologi ini hanya berhak untuk para Nabi dan Rasulnya saja, yang mendapatkan bimbingan langsung dari Allah untuk menjalankan hak progretifnya, termasuk dalam politik-negara, dan bukan pada manusia biasa. (ad-Din wa Addaulah; Cairo: Nasyr City, 1995, h. 6-7).
Kelima, jika HTI yakin pendirian khilâfah adalah termasuk kewajiban pokok agama, dia harus mampu menunjukkan dalil muhkam dari sumber primer yang bersifat qath’î, baik yang tsubut maupun dilalah. Seandianya ditemukan keduanya, maka pertanyaan selanjutnya adalah syariat yang mana? Tafsir siapa? Untuk konteks apa dan kapan? Daftar pertanyaan ini penting diajukan, sebab kata Ibnu Aqil, syariat itu amat beragam, ada yang rigit dan fleksibel, kendati agama satu, tapi penerapan untuk mencapai keadilan bisa beragam.
Katanya; Addin wahid, wasyariatu mukhtalifah? Ini belum lagi jika kita komparasikan dengan sistem negara. Apakah bentuk khilâfah itu? Monarkhi murni? Teokrasi? Teodemokrasi? Atau apa?
Karena problem-problem mendasar itulah, Imam Qurthûbî mengakui metode pengangkatan pemimpin dan bentuk negara bersifat dinamis, dialektik dan proposional, terhadap keadaan dan semangat zamannya, sebagaimaan bentuk dan rupa-rupa suksesi kekuasaan yang berlangsng di antara para Khulafâ’ Râsyidûn.
Bahkan, Imam Qurthûbî menyatakan seandainya pemimpin meraih kekuasaan dengan cara kudeta, dia tetap sah sebagai pemimpin dan wajib dipatuhi, selagai perintahnya demi tegaknya hukum dan keadilan bersama. (Tafsîr al-Jâmi’ li Ahkâm al-Qur’ân. Beirut: Dâr al-Kitâb al-Arabî, 2008, juz I, h. 311). Pandangan ini serupa dengan ijtihad Hujjatul Islam Imam al-Ghazali dan Imam Mawardi.
Untuk itulah, sebagai pertanyaan atas tuntutan zaman, konsep negara bangsa (nation-state) adalah jawabannya.
Sebagaimana negara kita punya ideologi Pancasila, sebagai pilihan ideal, karena negara kita, selain multi-etnis, juga multi-religi dengan bentuk negara demokrasi. Selagi umat bebas menjalankan agamanya, serta keadilan hukum dan kesejahteraan umat dijadikan tujuan utama, maka sistem politik apapun dapat dianggap telah "berjiwa Islami."
Tentu saja pemikiran ini bertolak belakang dengan ormas-ormas islam-radikal, seperti HTI yang masih berhalusinasi tentang era Khalifah yang sudah kadar luasa.
Dan, atas dasar itulah, kami menyimpulkan, bahwa Tuhan, sebenarnya tidak punya negara dan tidak butuh negara. Sebagai makhluk di bumi, manusialah yang membutuhkan negara sesuai takdir sejarahnya masing-masing. Wallahu'alam bishawab.
Cirebon, 11 Agustus, 2019.
*Alumnus Al-Azhar, Pengasuh Pondok Pesantren Bina Insan Mulia, Cirebon dan Wakil ketua Rabhita Ma'hahid Islamiyah PBNU, Periode 2010-2015.
Tribuners adalah platform jurnalisme warga. Untuk berkontribusi, anda bisa mengirimkan karya dalam bentuk berita, opini, esai, maupun kolom ke email [email protected]
Konten menjadi tanggungjawab penulis dan tidak mewakili pandangan redaksi tribunnews.com.



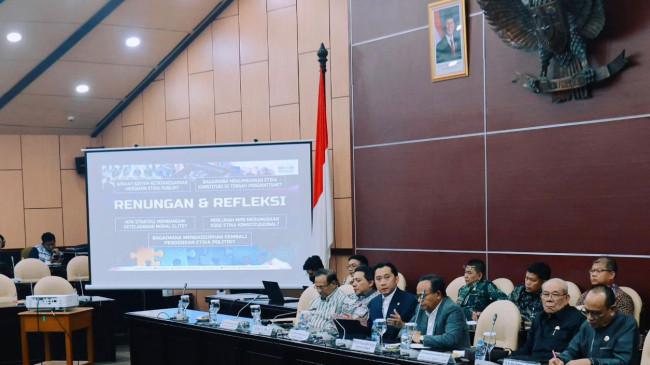
![[FULL] Ramai Desakan MBG Dihentikan Imbas Keracunan Massal, Pakar: Perbaiki, Jangan Ditutup-tutupi!](https://img.youtube.com/vi/Dwu9kx1Eo6Y/mqdefault.jpg)










